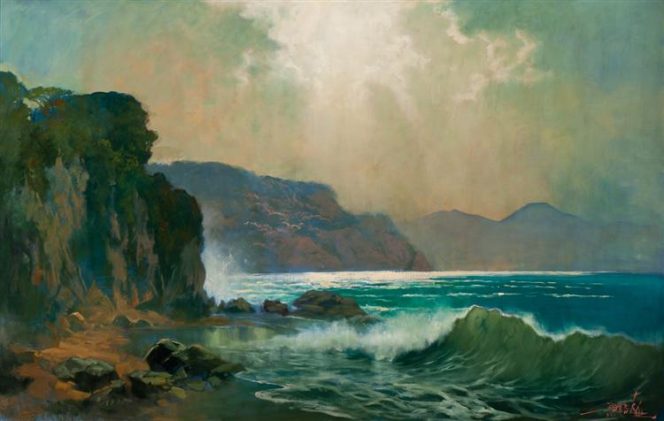oleh:
Aidil Auliya
(*) Disampaikan dalam Pidato Kebudayaan di Pustaka Steva, Padang, 17 September 2025.
Tuan dan puan yang saya rasa begitu bijak bestari!!!
Ketek indak disabuik namo, gadang indak diimbau gala. Disusun sepuluh jari, ditegakkan kepala untuk bersawala di depan tuan dan puan tanpa merasa paling “bermoral”. Ya, “bermoral”. Saya agak kikuk menggunakan kata bermoral itu. Terkadang, moralitas hanyalah persepsi yang dibangun untuk membungkus mental hipokrit. Kata Mochtar Lubis di dalam pidato kebudayaannya pada tanggal 6 April 1977 di Taman Ismail Marzuki, salah satu ciri Manusia Indonesia adalah hipokrit. Munafik!!!
Tuan dan puan!!!
Bentala Minangkabau tampak lindap akhir-akhir ini. Riuh sekali di media sosial tentang pemengaruh yang gandrung bicara moralitas. Memang, jamak di media sosial konten-konten jangak yang berisi makian yang terasa jijik untuk didengarkan. Tak termakan oleh anjing, tak tersudu oleh itik. Saya hanya pura-pura mengatakan itu, biar tidak dikatakan candala pula. Tentu, saya masih butuh dikatakan bermoral dan menjaga “Marwah Minangkabau”
Tapi inilah kenyataannya. Di media sosial sekarang tersaji perangai orang Minangkabau yang diwujudkan dalam bentuk yang berbeda. Minangkabau sebagai industri intelektual seakan-seakan sudah tergadai oleh perkembangan teknologi.
Laki-laki Minang kadang hadir dengan wujud gemulai seperti tanpa tulang sambil membasah-basahi bibir menarasikan konten. Saya sedang tidak menistakan kodrat alamiah, tapi hanya seolah-olah berdiri pada asas kepatutan. Ada pula yang bercarut tak karuan padahal umur sudah diambang akhir. Kadang kala para Datuak dan Mamak tampil ke muka khalayak dengan bercarut pungkang di media sosial. Beberapa Tuangku dan Buya, ikut mempertontonkan ilmu agama yang tak seberapa.
Lebih nahas lagi, saya ketemu sebuah konten seorang anak kecil yang bercarut pada ayahnya, lalu menginjak piring makan ayahnya. Kalau saya tidak salah telisik, konten itu diproduksi di Simalanggang, Luhak Lima Puluh Kota. Dekat dari kampung Syekh Saad Mungka, salah seorang ulama besar tasawuf Minangkabau pengamal tarekat Naqsyabandiah. Dekat pula dengan kampung Tan Malaka, Bapak Pendiri Republik. Konten- konten seperti itu tidak sedikit jumlahnya. Silakan tuan dan puan cari sendiri.
Tuan dan Puan yang dihormati di kaum masing-masing!!!
Tampaknya, telah terjadi bandwagon effect dalam pembuatan konten media sosial. Mengikuti sesuatu hanya karena banyak orang lain yang melakukannya. Psikologi di baliknya adalah keinginan untuk “berenang mengikuti arus” dan menjadi bagian dari mayoritas atau tren yang sedang popular. Ketika sebuah konten menjadi viral dan banyak ditonton, para kreator melihat hal itu sebagai “bukti” bahwa konten semacam itu harus direpetisi. Mereka kemudian ikut membuat konten serupa untuk masuk dalam pusaran popularitas sembari berharap mendapat sejumput perhatian. Alih-alih menjadi katalisator kultural, mereka justru sedang menyiapkan pusara terhadap nilai-nilai kebudayaan.
Efek bandwagon didasarkan pada mekanisme psikologis yang disebut bukti sosial “social proof”. Kecenderungan menganggap suatu tindakan lebih benar atau lebih diinginkan jika orang lain juga melakukannya. Perilaku orang lain dijadikan sebagai pedoman untuk bersikap, terutama dalam situasi yang ambigu dan paradoks.
Media sosial mana yang tak ambigu? Jumlah view, like, dan share yang tinggi berfungsi sebagai social proof yang kuat. Bagi penonton, ini adalah penanda bahwa “konten ini menarik, karena banyak yang menonton”. Bagi kreator, ini adalah penanda bahwa “membuat konten seperti itu adalah ide yang bagus, karena sudah terbukti diminati”. Anak-anak sekarang menyebutnya FOMO. Perasaan cemas atau khawatir tidak ikut serta menikmati tren-tren popular. Seorang kreator mungkin merasa FOMO jika tidak ikut membuat konten yang sedang tren. Takut ketinggalan momentum, kehilangan peluang untuk mendapatkan subscriber baru, atau terlihat tidak turut ambil bagian.
Fenomena ini diperkuat dengan kekuatan algoritma. Algoritma dirancang untuk mempromosikan konten yang sudah terbukti popular (high engagement). Jadi, ketika sebuah tren muncul, algoritma akan aktif merekomendasikan konten-konten serupa lainnya, yang pada gilirannya memicu lebih banyak kreator untuk membuat konten serupa. Terciptalah sebuah siklus setan yang sulit untuk diputus.
Algoritma media sosial telah menciptakan ekosistem baru di mana konten yang memicu emosi kuat seperti kemarahan dan kebencian (bahkan kata-kata tak bijak) mendapatkan perhatian lebih besar. Dalam sistem ini, makian dan konten provokatif sering kali lebih cepat viral daripada konten yang mendidik dan mencerahkan. Atau jangan-jangan kitalah yang salah, terlalu banyak berharap. Terlalu optimis dengan perkembangan zaman. Apakah tepat mencari moralitas di rimba media sosial? Bagaimana pula bisa mencari suatu yang mendidik dan mencerahkan di dunia para budak algoritma? Sungguh jentaka.
Kita semua sekarang mungkin sudah terpenjara dan menjadi budak algoritma. Algoritma telah menjelma menjadi niniak mamak orang Minangkabau. Generasi muda bermamak pada media sosial. Pendidikan mamak virtual itu ternyata berhasil melahirkan mulut-mulut, ujung-ujung jemari, dan benak yang tak pernah tersentuh peradaban. Budaya generasi baru Minang sedang terpampang nyata di media sosial, tergelak mendengar carutan dan makian sembari berjoget bahagia dengan status Minang-nya. Melakukan perbuatan tidak merdesa tanpa beban. Bersuka cita sambil mengangkat keranda peradaban Minangkabau. Fenomena ini tentu saja tidak hanya terjadi di Minangkabau, tetapi secara global. Namun, bagi masyarakat Minang yang katanya memiliki warisan budaya yang kaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, perubahan ini terasa sangat kontras.
Kata pemengaruh yang aktif mengkampanyekan ini di media sosialnya, di Minang ini ada kato nan ampek: kato mandaki, kato manurun, kato malereng, dan kato mandata. Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. Iya, sangat benar. Tapi, bukankah Minangkabau hanya tinggal dalam memori kolektif? Minangkabau sudah diambang senja. Nilai-nilainya tetap dihafalkan dan dilafalkan, tetapi belum lagi akan menjadi laku kolektif masyarakat. Dianggap usang, tidak popular, ketinggalan zaman, dan berangsur musnah dalam museum- museum yang tak pernah dikunjungi. Ini bukan insinuasi apalagi halusinasi, ini adalah pengakuan yang harus diucapkan.
Kita yang salah, berharap falsafah adat dan norma-norma kultural sebagai panduan dalam berkomunikasi, tapi tak pernah sadar bahwa mamak-mamak virtual tidak mengajarkan seperti itu.
Kamanakan barajo ka mamak
Mamak barajo ka pangulu
Pangulu barajo ka mupakat
Mupakat barajo ka algoritma
Algoritma badiri ka nan punyo.
Kita yang tumbuh di era digital ini mungkin menganggap bahwa apa yang dilihat di media sosial adalah norma yang berlaku. Nilai-nilai “alun takilek lah takalam” seakan menemukan bentuk barunya dalam konsumsi konten digital yang tanpa seleksi. Generasi muda Minang kini menghadapi tantangan identitas yang kompleks. Di satu sisi, diwarisi nilai-nilai yang katanya luhur khas budaya Minang dan menjunjung tinggi sopan santun. Di sisi lain, mereka terpapar dengan konten-konten digital yang sering kali bertolak belakang dengan nilai-nilai tersebut. Lambat laun, nilai-nilai yang hidup di media sosial tersebut diinternalisasi secara serampangan. Popularitas yang dihasilkan dari konten provokatif dan penuh makian dianggap biasa dan normal. Jangan heran kalau nilai ini akan berwujud pada perilaku primitif dan hanya mengikuti kebenaran pada dengkul masing-masing. Babana ka ampu kaki!!
Lalu bagaimana dengan wanita Minang nan anggun itu sekarang? Cobalah masuk ke labirin media sosial. Tuan dan puan akan susah mencari jalan keluar, terjerembab dalam limbah para wanita Minang yang tak segan lagi bercarut pungkang. Semua kata-kata nista dihamburkan dengan dalih hanya konten dan hiburan. Sebagai limpapeh rumah nan gadang, barangkali limpapeh itu sudah limbung kalau tidak mau disebut patah. Dihantam badai peradaban. Dikunyah teknologi yang terkendalikan. Sakali aia gadang, sakali tapian barubah. Kita terpungkang dalam jenggala kata-kata yang dianggap nista.
Dalam konteks perubahan sosial yang begitu cepat ini, peran ninik mamak dan institusi adat seharusnya semakin penting. Bolehlah kita berharap mereka akan menjadi penjaga gawang nilai-nilai budaya dan penuntun bagi generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman. Namun, sering kali kita melihat bahwa ninik mamak dan institusi adat justru terlihat gamang menghadapi perubahan ini. Ada yang terlalu kaku dan menolak semua bentuk perubahan, ada pula yang terlalu lentur hingga kehilangan prinsip. Malah ada pula yang memperdagangkan gelar adat demi kepentingan yang tidak punya jangka prioritas itu, lalu muncul sebagai penjaga moralitas. Paradoks, bukan? Memupuk harapan tentu boleh-boleh saja, tetapi harus siap- siap juga patah arang dengan harapan yang tak kunjung terwujud.
Tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan, bukanlah sekadar “instrumen pelengkap dalam struktur adat”. Di mana para alim ulama, niniak mamak, dan cadiak pandai nan gadang basa batuah? Mereka bukan tak berkata dan bertindak. Hanya saja zaman telah berubah. Peradaban tak ubahnya seperti pasar malam saja kata Pramoedya Ananta Toer, kebisingan suara di media sosial mengalahkan kualitas isi kepala. Siapa pula yang mau mendengar orang yang tak banyak pengikut media sosialnya? Otoritas dan kepakaran telah berganti ukuran, tergantung pada siapa yang berkata dan berapa banyak pengikutnya. Itulah penentu kebenaran dan moralitas!!!
Kalaulah Rene Descartes, filosof asal Prancis itu masih hidup hari ini, maka sudah tersaji argumen, “aku viral maka aku ada.” Makian demi makian berkayau di media sosial. Jagal-jagal kata menjamur dan menguliti martabat diri dan kaumnya. Ini semua bukan untuk menjaga “marwah Minangkabau”. Toh, marwah kebudayaan itu sudah menjadi barang langka yang hanya diidamkan tapi tak lagi bisa didapatkan.
Tuan dan Puan yang berbudi
Fenomena “alek caruik” di medan maya ini adalah cermin retak dalam budaya Minang. Para penikmat, pelaku, dan bahkan pengomentar, adalah kumpulan pengkhianat yang bersorak riang di atas puing-puing peradaban sendiri. Mengecam budaya caruik sembari menyuguhkan hiburan-hiburan picisan yang terkadang lebih nista. Menjerit lantang menolak cacian, namun lamat-lamat menari-nari di atas panggung kehinaan dengan konten yang kosong dan menyesatkan.
Para munafik tulen! Berteriak lantang tentang moral, sambil memperjualbelikan aib dan kebodohan demi sesuap like dan seteguk view. Menolak budaya caruik hanya karena ingin disebut beradab, namun tak segan menyajikan tontonan yang merendahkan akal budi dan semua itu dibungkus rapi dalam kemasan “hiburan”.
Kita semua telah berkhianat. Berkhianat pada sebongkah warisan. Berkhianat pada raso jo pareso yang telah digantikan oleh raso nan dangkal dan pareso nan palsu. Kita jual Minang dengan harga murah sembari menukar emas dengan loyang. Dek ulah kilek loyang datang, intan tasangko kilek kaco.
Beberapa pemangku adat telah bergeser menjadi ornamen bisu! Menjadi hiasan di upacara adat dan kehilangan wibawa serta nirguna. Sibuk berdebat tentang sako dan pusako, tetapi tuli terhadap jeritan zaman. Orang-orang seperti itu layak dipurukkan ke kubangan kerbau dan dicemplungkan ke dalam lumpur realita agar melek. Jangan-jangan sekarang seperti kerbau yang terlepas dari tali, berlari tanpa arah dan melenguh tanpa makna. Tak lagi menjadi payung panji bagi kemenakan, malah jadi beban yang diam-diam mempercepat tenggelamnya sebuah peradaban.
Barangkali kita adalah investor utama kebangkrutan budaya. Menggadaikan budi untuk konten dan menukar kearifan dengan komentar. Minangkabau menjelma jadi museum tanpa pengunjung, sementara kita asyik memamerkan sampah di etalase maya.
Kelak, ketika Minang benar-benar menjadi sekadar dongengan, kita akan jadi generasi terakhir yang menyaksikan senja itu. Kaburlah Minang, tinggallah para pemangku adat yang berkubang dalam lumpur kebanggaan artifisial. Para konten kreator itu akan dikenang sebagai algojo yang dengan senang hati memenggal akar budaya sendiri.
Apalah akal kita? Kekuasaan hari ini ditentukan dari kuota dan pengikut yang bahagia dengan konten-konten seperti itu. Mereka tetap berdalih demi hiburan. Siapa yang terhibur? Benak seperti apa yang bergairah memancarkan hasrat mendengar dan melihat fenomena itu? Kita hanya bisa termangu mendengar ocehan-ocehan tersebut. Rasa-rasanya, “mambangkik batang tarandam” tidak lebih penting daripada “mambangkik banak tarandam”. Ini bukanlah elegi, hanya ocehan perintang-rintang hati.
Meminjam istilah M. Hatta, Kita sedang mendayung di antara dua karang. Menormalisasikan dengan dalih kebebasan dan penanda kemajuan zaman atau berdiri melawan atas nama adat baso basi, muluik manih kucindam murah, raso jo pareso, dan alue jo patuik. Alih-alih berenang diantara dua karang, justru kita berpotensi diselimuti bayang-bayang kemunafikan.
Epilog
Tuan dan puan.
Setiap kata pasti ada gelanggangnya. Kata orang-orang “ngakademisi” makna sebuah kata sangat tergantung pada konteksnya.Dalam khazanah linguistik kebudayaan, kata dalam judul tulisan ini mendiami dua kutub makna yang saling bertentangan secara diametral. Di satu sisi, kata ini berfungsi sebagai umpatan puncak. Sebuah kata tabu dengan daya ledak emosional yang luar biasa. Pengucapannya dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap norma kesopanan. Penggunaannya dalam percakapan sehari-hari menandakan luapan emosi ekstrem dan dianggap sangat ofensif.
Kata-kata carut itu masuk dalam kategori kata tabu. Tabu dalam KBBI diartikan sebagai hal yang tidak boleh disentuh, diucapkan, dan sebagainya karena berkaitan dengan kekuatan supernatural yang berbahaya; pantangan; larangan. Namun, dalam kebudayaan, kata tabu memiliki fungsi yang jamak. Berfungsi untuk mengungkapkan pelbagai emosi seperti kemarahan, penghinaan, kekecewaan, ejekan, provokasi, dan atau menunjukkan keakraban dalam konteks tertentu. Fungsinya tergantung konteks dan gelanggang pengucapannya.
Bercarut mungkin adalah salah satu upaya untuk meminjam kekuatan dari sebuah kata-kata tabu. Emma Bryne dalam bukunya “Swearing is Good For You”, membuat beberapa kesimpulan: Pertama, sekelompok atau individu yang berbagi leksikon vulgar cenderung bekerja sama dengan lebih efektif, lebih dekat, dan lebih produktif. Kedua, mengumpat dapat membuat pikiran lebih agresif dan secara paradoks dapat meminimalisir kekerasan fisik.
Di sisi lain, makna kata ini sangat berbeda secara teknis dalam penerimaan batin orang Minangkabau. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan, pantek sebagai nomina (kata benda) yang berarti “pasak; paku semat.” Kata kerja turunannya, memantek, didefinisikan sebagai “melekatkan (kayu, bambu, dan sebagainya) dengan pantek; memasak”.
Barcarut pungkang merupakan hal alamiah, artefak kebudayaan yang bisa mengajarkan banyak hal, dari cara kerja otak, pikiran, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Walaupun bercarut adalah leksikon yang primitif yang selalu berevolusi, namun carut adalah sinyal sosial yang kompleks yang sarat dengan signifikansi emosional dan budaya. Kitalah yang memutuskan apa yang tabu dan tidak, dan kata tabu mana yang cocok untuk dilanggar.
Meminjam pemaknaan KBBI, Minangkabau memang harus dipantekkan agar dia menghujam ulu jantung Homo Minangkabaunesis. Tidak lagi dihafal dan dilafal, tetapi hidup dan dipasakkan dalam roh kebudayaan untuk menyangga peradaban. Atau memang kata itu harusnya dieja dan diteriakkan dengan lantang sesuai dengan makna bahasa Minang untuk meluapkan kenestapaan hati sembari berharap memberi hukuman ta’zir pada mamak, kaum, dan suku si tukang caruik yang tidak tahu tempat. Entahlah !!! (*)
Aidil Aulya, Dosen UIN Imam Bonjol. Tulisannya tersebar di beberapa media massa, seperti Kompas.com, Langgam.id, dan lain-lain.