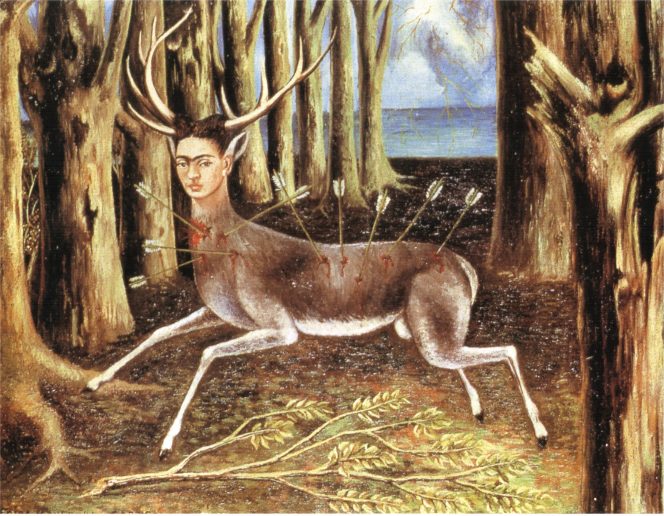Oleh Fatris MF
Caruik; berkata-kata cabul, makian, umpatan, carut-marut, keji, kotor. Begitu kamus mencatatnya. Seberapa kotor kata-kata itu? Bacaruik, seberapa buruknya perilaku itu hingga bisa dianggap meresahkan?
Sebelum para konten kreator, pejabat, orang-orang yang merasa bermoral dan bermartabat tinggi ramai mempermasalahkan “para pencaruik TikTok” di akun-akun mereka, pada tahun 2020 silam, Walikota Mahyeldi, yang sekarang menjadi Gubernur Sumatera Barat dua periode, terlibat cekcok dengan ibu-ibu pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang. Saat bertengkar, Emi, nama perempuan pedagang kaki lima tersebut, mampacaruikan Sang Walikota. Ada kata “pantek” yang keluar dari mulutnya. Tapi, kata “pantek” itu tidak hanya habis di Pantai Padang saja, ia memiliki sayap, berentet ke relasi kuasa yang berlapis. Sebagaimana dituliskan banyak media saat itu, ibu tersebut didatangi oleh seorang lelaki bernama Haji Maidestal Hari Mahesa. Tak lama setelah kedatangan haji muda yang gagah dan berpengaruh itu, Emi klarifikasi di media sosial dan meminta maaf atas kesalahannya “mampacaruikan” Wali Kota. Tentu saja penuh tekanan, ingat, Maidestal Hari Mahesa adalah [mantan] anggota DPRD Padang tiga periode. Apa daya seorang perempuan pedagang kaki lima di hadapan anggota dewan yang terhormat tiga periode? Puaskah para moralis dunia maya atas permintamaafan Emi tersebut? Lihat, bagaimana borjuis-borjuis kecil di kota centang perenang ini mengedukasi warganya dengan cara yang licik, men-suci-kan walikotanya hingga ia tidak pantas menerima luapan emosional dari warganya sendiri? Tidakkah patut dipuji tindakan tersebut untuk mengingatkan bahwa Padang sebagai kota madani harus bebas dari ‘caruik’? Ingat, caruik itu bukan budaya Minangkabau! Lantas, budaya siapa? Budaya siapa saja asal bukan Minangkabau.
Bacaruik tentu bukan tindakan terpuji, alih-alih bijaksana. Jika ada yang bilang bacaruik itu terhormat, itu tidak dapat dibenarkan kewarasannya. Akan tetapi, di sisi lain, tidakkah bacaruik adalah muara dari kekesalan, luapan emosional? Bacaruik, berkata-kata kotor, mengumpat, memaki, adalah juga senjata terakhir orang-orang lemah untuk memprotes keadaan, masyarakat akar rumput yang tidak tahu siapa yang hendak membela hidup mereka di kota madani ini. Wilayah-wilayah yang orangnya suka bacaruik, kata seorang pejabat, adalah wilayah yang pendidikannya rendah. Bukannya menyetarakan pendidikan, malah fokusnya ke caruik.
Hal lain tentang caruik, pernah dikemukakan oleh seorang profesor psikologi yang juga seorang penulis buku berpengaruh Black Sheep: The Hidden Bennefits of Being Bad. Richard Stevens, bilang bahwa mengumpat dan memaki dapat membantu orang menahan rasa sakit dan meningkatkan kekuatan fisik [untuk bertahan hidup]. Singkatnya, orang-orang tersakiti akan memaki, karena makian adalah bentuk pemberontakan spontan pada diri manusia. Dan di Minangkabau yang egaliter, yang setara, adalah sarang segala pemberontakan, orang-orang yang disakiti. Setidaknya sejak 400 tahun lalu dan berakhir setelah PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia kalah.
Pada masa kolonial, ketika pemerintah Belanda mengeluarkan aturan pajak yang mencekik, pemberontakan berkobar. Dari Kamang, Manggopoh, hingga ke Padang. Banyak yang mati. Perang Belasting, atau perang pajak itu kemudian melahirkan banyak kata makian: kalempong! kalapia! karambia! (karena pohon kelapa juga dipajak oleh Belanda, maka setelah itu tidak menutup kemungkinan akan diterapkan pajak terhadap alat kelamin). Benarkah demikian?
Masih di masa kolonial. Saat perang melanda, masyarakat lapar, wabah kolera serta-merta menjangkiti berbarengan. Kematian di sana-sini. Dari situasi panik oleh wabah kolera itulah terbentuk umpatan, makian, kutukan: “kalera!”. Kata itu, tentu berbeda terbentuknya dengan kata makian “anjiang” atau “hanjiang” yang jauh lebih dulu hadir mengisi “kamus kata-kata jorok Minangkabau”. Misalnya di poster-poster perlawanan masa kemerdekaan, ada “anjing penjajah”, Batalion V KNIL disebut Andjing NICA. Kata ini tentu cocoknya diarahkan pada orang yang mentalnya seperti anjing: setia pada siapa yang memelihara mereka, menjilat siapa saja yang memberi mereka makan dan akan menjaga harta serta marwah tuan mereka dengan cara menggonggong, kalau perlu menggigit. Bukankah kata “[h]anjiang” ini yang harusnya lebih abadi sebagai makian di Minangkabau yang bermarwah sekarang ini, njirr?
***
Baru-baru ini tiba-tiba ramai para polisi moralis, social justice warrior, mengutuk para “caruikers” “tukang caruik” di media sosial karena dianggap menciderai budaya Minangkabau. Jika dilihat konten para tukang caruik ini juga lucu, kadang juga memualkan. Orang tua mana yang tega kalau konten-konten penuh caci maki seperti itu dilihat oleh anak-anak mereka yang masih belia, calon pewaris kebudayaan Minangkabau yang luhur?
Para konten kreator yang mengaku punya tanggungjawab moral itu merasa bersuara sekarang melawan konten kreator “pacaruik” dengan alasan “demi menjaga marwah Minangkabau”. Salah satunya saya simak kata-kata di akun Uda Rio (@udario.id) misalnya:
Salamoko awak cuman diam mancaliak konten-konten caruik di live TikTok. Cuman, makin lamo makin banyak, makin dianggap biaso, makin meresahkan. Dan iko masalah serius. Di Minang ko ado kato nan ampek, kato mandata, kato mandaki, kato manurun. Adaik basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Nah, itu yang lah ndak ado kini…Jadi ayok samo-samo kita jago marwah Minangkabau.
Simak ultimatum [maksudnya ceramah] Uda kita ini soal kato nan ampek, terus adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Apa hubungannya kato nan ampek, adat basandi sarak, marwah Minangkabau dengan caruik, Uda? Apakah para pancaruik itu bacaruik di dekat ninikmamaknya yang harusnya dia pakai kato mandaki, atau di hadapan rangsumando-nya yang harus ia gunakan kato malereang atau di dalam rumah gadang nan sambilan ruangnya, atau dalam batagakgala?
Soal adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah yang dibilang lah ndak ado kini: terus, kapan ia ada? Kalau memang ia sudah tidak ada, seperti kata Uda, mengapa mengajak menjaga marwah Minangkabau. Menjaga sesuatu yang sudah tidak ada, bagaimana caranya?
Mari kita anggap marwah itu benar adanya. Saya agak terenyuh mendengarnya, sebab belum pernah saya membaca bahwa, misalnya, Hamka pernah mengatakan “menjaga marwah Minangkabau”, maka ide soal menjaga marwah Minangkabau ini perlu didukung berbagai pihak dan stakeholder. Pertanyaanya, sebegitu rendah dan lemahkah marwah Minangkabau hingga ia begitu mudah terciderai oleh caruik-pungkang-caci-maki? Bukankah marwah suatu bangsa, suku, Minangkabau misalnya, terletak pada nilai-nilai yang diwariskannya: egaliternya, filosofinya, dialektikanya misalkan. Nah, marwah mana yang dianggap terciderai oleh konten berisi caruik? Dari komentar-komentar yang saya baca di media sosial, ada konten kreator yang ingin melakukan gerakan moral melawan konten caruik. Serius? Gerakan moral? Manifestasi dari sikap yang bernilai kemanfaatannya, itu bukan yang disebut sebagai gerakan moral? Salut terhadap gerakan moral ini. Ada lagi yang mengatakan melawan konten-konten caruik, karena para “caruikers” mendapat gift. Mana yang benar?
Jika hanya soal ‘gift’, tidakkah para penjilat, influencer, yang bernaung di bawah ketiak pemerintahan korup juga telah mendapat ‘gift’, bahkan lebih dulu ketimbang para “caruikers”? Bedanya, para penjilat kekuasaan berselimut dengan topeng kesopanan berbalut basa-basi, benarkah begitu? Terus, yang dikatakan “salamoko awak diam”, bagaimana melihat fenomena ini? Kalau gerakan moral yang dibilang konten kreator Minangkabau yang bermartabat itu adalah obat, mana yang harusnya diobati lebih dulu: karampang nan bakurok tapi tertutup oleh pakaian, atau jerawat di pipi yang terlihat khalayak?
Dengan begitu, mereka, para konten kreator itu, para pejabat yang ikut mengutuk para pencarut adalah penjaga marwah Minangkabau itu sendiri? Pertanyaanya, marwah seperti apa yang dijaga, yang mana? Caruik yang bagaimana yang bertanggungjawab atas terkoyak-koyaknya marwah orang Minangkabau?
Kalau marwah Minangkabau itu tidak hanya terletak pada egalitariannya, seperti kata Hamka, pada dialektikanya, tapi juga pada kesusastraannya. Beberapa tahun silam Gubernur yang suka berpantun spontan menerbitkan pantun-pantun buruk yang bukan pantun tapi ia namakan sebagai pantun, dicetak berjilid-jilid. Bukankah perilaku itu telah mengangkangi marwah Minangkabau itu sendiri, seakan capaian dari peradaban sastra orang Minangkabau terletak pada pantun-pantun cacat semantik tak keruan yang ditulis seorang gubernur? Jika marwah orang Minangkabau terletak pada hutan adatnya, tanah pusako-nya, bukankah penguasa telah merusaknya? Tidakkah apa yang terjadi di banyak tempat, seperti di Kapa misalnya, adalah hal yang paling nyata mengoyak marwah Minangkabau itu sendiri? Atau kita benar-benar telah mempraktekkan petuah tibo di mato bapiciangan, tibo di paruik bakampihan?
Tiga tahun silam, Teddy Minahasa diberi gelar kehormatan adat yang tidak tanggung-tanggung: Tuanku Bandaro Alam Sati, sementara untuk istrinya Puti Sibadayu. Siapa yang mengeluarkan gelar kehormatan itu? Tidakkah lembaga adat tertinggi sealam Minangkabau ini? Tidakkah ini normal saja? Siapa yang resah? Bukankah kalau nan kumuah disasah, nan baabu dijantiak?
Bagaimana mengatur ‘alua jo patuik’ di TikTok dan media sosial lainnya, apa tertera dalam tambo? Mencari kesucian dalam TikTok, adakah tidak sama dengan mencari air jernih di tengah air yang keruh? Terus, para “caruikers” diperangi atas alasan Minangkabau yang luhur dan bermartabat? Kapan? Bukankah kerja penghulu, para pemangku adat di dataran tinggi kerjanya madat, dan mabuk hingga memicu gerakan pemurnian yang bernama Padri? O, ini terlalu jauh. Kita kembali ke pangkal jalan
Para konten kreator, influencer, bicara soal alam takambang jadi guru. Kalau benar kita mengkaji ke alam, bukankah alam Minangkabau telah dirusak oleh para penguasanya? Tidakkah itu gajah di pelupuk mata namanya, wahai konten kreator yang bermoral? Kenapa tungau caruik di seberang lautan tampak?. (*)
Fatris MF, adalah seorang penggemar filologi dan sastra lisan yang bekerja sebagai periset dan jurnalis lepas untuk beberapa media, seperti DestinAsian Indonesia dan Koran Tempo. Buku-buku yang ia tulis merupakan kumpulan catatan perjalanannya ke berbagai daerah di Indonesia yang berfokus pada sejarah, isu lingkungan, serta pergeseran budaya dan pergesekannya dengan modernisasi. Dia menetap di Padang, Sumatera Barat. Buku-bukunya yang telah terbit, Merobek Sumatra (2015), Kabar dari Timur (2018), Lara Tawa Nusantara (2019), Hikayat Sumatra (2021), Indonesia dari Pinggir (2023), dan Di Bawah Kuasa Naga (2024). The Banda Journal (2021) bukunya bersama Muhammad Fadli menjadi salah satu Photobook terbaik versi Majalah TIME.