Dunia Busuk di Balik Layar Plenses Renee – Ulasan Novel Individutopia karya Joss Sheldon
Distopia Tingkat Akut, Peradaban yang Terlambat Direset, dan Kemanusiaan yang Kelak Dirindukan
Aku membayangkan betapa berisik sekaligus sepi (apa kata lain dari jenis sepi yang teramat sangat?) kehidupan Renee. Hidup di zaman yang ‘terlambat direset’, di mana kemanusiaan telah lama punah, dan teknologi berbasis AI menguasai segala lini.
Renee sejak bayi diasuh oleh robot Babytron yang menemukannya di sebuah emperan toko, beberapa saat setelah ibunya membuangnya. Lalu bunuh diri. Ayahnya adalah seorang pengemis—yang belakangan diketahui tepat sesaat sebelum kematiannya—di jalanan Kota London yang luluh lantak, penuh gunungan sampah, bangkai tikus, udara berbau busuk, dan langit muram terlapisi tebalnya debu polusi. Pemandangan itu terpampang telanjang tepat ketika Renee membuka layar Personal Lenses (plenses) miliknya yang selama ini memanipulasi realitas. Sebuah filter yang memproyeksikan dunia digital, semacam dunia kecil milik individu pemakainya. Dunia yang ia ciptakan sendiri dari pikiran yang termanipulasi.
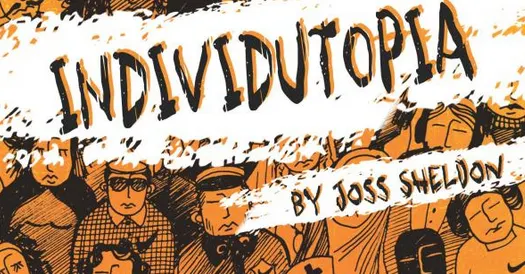
Individutopia by Joss Shelldon. Sumber Foto: Medium.com
Bertahun-tahun Renee hidup dalam dunia di balik layar Plenses. Menciptakan versi dirinya yang lain dalam rupa berbagai avatar. Hidup penuh desakan untuk berkompetisi dengan entah siapa (dan untuk apa?). Renee tidak pernah berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam Individutopia, orang-orang hidup untuk diri mereka sendiri. Hidup untuk bekerja. Memperoleh peringkat tertinggi dalam grafik yang mencatat apa saja—mentalitas berkompetisi dan ingin lebih baik dari orang lain sudah lama eksis, bahkan sistem pendidikan kita turut andil menciptakan mentalitas semacam ini seperti sistem ranking misalnya—bekerja amat keras dan mendapat upah yang nilainya jauh lebih kecil dibandingkan persentase utang yang terus bertambah dari detik ke detik. Ingat! Dalam Individutopia, tak ada fasilitas publik. Setiap keping bumi dan langit dimiliki secara pribadi. Bahkan bernapas pun kau harus bayar!
“… dan setiap pantai dipagari” kutipan ini mengingatkan kita pada kasus pagar laut. Memunculkan racauan pikiran: jangan-jangan negeri ini sudah tergadai ke pihak individu, dan sistem pemerintahan serta segala perangkatnya, bekerja untuk kepentingan pribadi…
Dan sebagaimana penduduk Individutopia, kita dibuat sibuk dengan hal remeh-temeh dan tetek bengek lainnya—yang jauh dari substansi kehidupan—agar kita rakyat berderai tidak bangkit dan menggulingkan oligarki. Begitulah individu yang hidup dalam distopia mengerikan di Kota London yang lebih layak punah. Lewat layar plensesnya, setiap saat mereka diingatkan dengan jumlah utang yang terus bertambah, penawaran produk baru yang sesungguhnya tidak dibutuhkan namun sangat ingin dimiliki, serta desakan untuk menjadi peringkat teratas dalam grafik yang membuat setiap orang merasa haus kompetisi meski melelahkan. Bekerja teramat keras agar mampu memiliki—dan ironisnya—dikuasai barang-barang yang diperoleh dari kerja keras tak berkesudahan itu.
“Seolah-olah dia diberi imbalan karena tidak lagi mempertanyakan sistem, karena cukup pintar bekerja, tapi tidak cukup pintar mempertanyakan mengapa.” (halaman 85)
Ketika kebebasan diberikan tanpa batasan, kapitalisme menjadi raksasa yang sulit ditaklukkan. Kesenjangan sosial bagai langit tertinggi dan palung terdalam bumi. Menciptakan manusia konsumtif lewat berbagai narasi dan slogan. Manusia dikotak-kotakkan berdasarkan apa saja. Kemudian berdasarkan pengkotakan tersebut, diciptakan semacam selera yang diakui milik bersama dan mewakili suatu generasi yang telah dilabeli. Tiap manusia dalam kotak percaya bahwa mereka harus mengikuti tren apa saja agar ‘diakui’. Entah kenapa mereka mau saja dinamai dan menerima itu sebagai diri mereka.
Orang-orang bekerja (mereka pikir mereka bekerja sebagaimana orang-orang bekerja untuk mengumpulkan kekayaan), padahal mereka bekerja hanya agar bisa memuaskan perilaku konsumtif semata. Diperdaya oleh sistem kapitalisasi yang melanggengkan perbudakan—di mana orang-orang bekerja dan diupah untuk sekadar bertahan hari demi hari, kata Percy Shelley.
Kembali kepada Renee, gadis yang sibuk bekerja dari waktu ke waktu, maksudku, bekerja apa saja seperti memecahkan dan memperbaiki barang, mengelupas dan memasang ubin di tempat semula, memindahkan perabotan dari satu ruang ke ruang lain, kemudian diletakkan kembali di tempat semula, melakukan lompatan bintang, dan segala jenis pekerjaan sia-sia lainnya.
Sia-sia?
Di dalam Individutopia, melakukan hal yang sia-sia sekalipun bahkan jauh lebih baik daripada tidak melakukan apapun sama sekali. Meski kau terus bertanya, apa makna dari semua itu? Era di mana segala jenis bidang pekerjaan telah diambil-alih AI, manusia akan melakukan apa saja agar tetap bekerja, meski itu tak berguna. Bekerja seumur hidup hanya untuk membayar utang-utang yang terus bertambah, serta demi memiliki properti yang tak akan pernah mampu dimiliki.
Di tengah alienasi, ia mulai mempertanyakan makna keberadaan diri. Dikitari realitas palsu yang menjemukan, ia mulai mempertanyakan kehidupan.
“Mengapa aku harus memikul tanggung jawab pribadi? Masalah-masalahku bukan kesalahanku, mereka diciptakan oleh sistem; sistem kotor ini, yang mengisolasiku dari Aku-Lain; menempatkanku di bawah tekanan untuk bekerja, bersaing, dan mengonsumsi…” (halaman 119)
Dan inilah yang dinanti-nantikan oleh ‘Sang Narator’, yang menciptakan dunia simulasi untuk satu tujuan tertentu. Di mana hampir seluruh penduduk Kota London yang luluh lantak mengalami depresi, menyerah, lalu bunuh diri—tak mampu hidup di bawah sistem Individutopia yang penuh kompetisi, interaksi palsu, dan nihil empati—Renee bertahan.
Setelah melewati berbagai pergulatan dalam dirinya, bertarung dengan pikiran-pikirannya sendiri, pikiran yang selama ini ia yakini paling benar, tidur dan terbangun hanya untuk menghadapi realitas ‘mahagila’ yang tercipta dari ilusi visual di balik layar plensesnya, sesuatu dalam diri Renee mulai menggeliat. Pintu kesadarannya mulai terbuka. Ia berontak.
Realitas di Balik Layar Plenses
Renee melepas layar plensesnya, dan ternganga melihat realitas telanjang di hadapan matanya tanpa filter. Kota London yang lebih mirip onggokan sampah. Bau tengik. Udara kuning kelabu menutupi biru langit. Tikus-tikus berkeliaran. Dan kucing mati yang selama ini ditendangnya setiap kali melewati satu koridor, ternyata adalah bangkai manusia dengan perut terburai penuh ulat. Barangkali bangkai dari salah satu manusia kalah yang memilih bunuh diri—dan bunuh diri di Individutopia telah menjadi suatu kewajaran, sesuatu yang telah dinormalisasi.
Renee sangat ingin berinteraksi dengan Aku-Lain. Begitu ia sebut diri di luar dirinya. Sepanjang usia hidup dalam dunia yang terindividualisasi, membuatnya tidak mengerti konsep Aku-Kau Kita-Mereka.
Dalam upaya melepaskan diri dari kungkung pikiran yang selama ini terbentuk dari sistem yang diciptakan dan dunia virtual yang ia yakini sebagai kebenaran, Renee menemukan sebuah tempat yang tak pernah ia kira ada. Alam terbuka, tempat segala sesuatu yang hijau dan berwarna-warni tumbuh mencuat dari tanah. Rumput-rumput hijau—yang dulu ia yakini bewarna biru—pohon-pohon yang menjulurkan buah-buahan.
Renee mengamati segala sesuatu dengan seksama, dan mempelajari bagaimana alam bekerja dengan prinsip-prinsipnya. Lalu menemukan semacam pemikiran-pemikiran revolusioner bagi seorang individualis sejati seperti dirinya selama ini, lalu menemukan semacam konsep filosofis tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan semestinya.
Semut kecil yang berkoloni mampu melawan sesuatu yang lebih besar dari tubuhnya; masyarakat kecil yang bersatu, bukankah semestinya juga mampu menggulingkan oligarki?
Di tengah realitas yang nampak aneh—sebab jauh berbeda dari realitas di mana ia hidup selama ini—Renee mulai meragukan realitas keberadaannya sendiri, khawatir dengan ketidakbermaknaan keberadaan. Membawa kita pada pikiran eksistensialisme. Ia menyaksikan bagaimana dunia yang jauh dari peradaban, alam mengambil-alih sekali lagi apa yang semestinya menjadi miliknya. Hukum keseimbangan tetap bekerja, ‘udara membersihkan diri dan kembali ke keadaan alami’. Renee seolah manusia pertama di bumi, sebelum peradaban. Dan dialah yang akan memulai!
“Kosongnya waktu membuka jalan menuju padatnya renungan diri,” (halaman 172)
Begitulah, tanpa layar plenses, tanpa alarm yang mengingatkannya pada deret angka utangnya yang terus bertambah, tanpa avatar-avatar atau hologram yang nyinyir menyampaikan informasi apa saja, penawaran-penawaran barang yang diproduksi tiada henti dan mempengaruhi calon konsumennya untuk segera memiliki, dunia terasa sunyi. Hening. Kepalanya menjadi ruang kosong yang memungkinkan dirinya mendengar suara dari dirinya yang lain. Dirinya yang sejati.
Ketika naluri kemanusiaan mulai tumbuh perlahan, ia merasa asing.
Di tengah hutan, Renee melepaskan segala pakaiannya. Ia hadir sebagai diri yang murni. Terlepas dari masa lalu. Ia telanjang kini. Lalu memakan apel yang setelah melewati pengamatannya, ternyata bisa dimakan dan menutupi rasa laparnya. Ia mendapatkan pengalaman memakan makanan yang sesungguhnya. Berinteraksi dengan beberapa makhluk lainnya, termasuk manusia. Makan apel hingga sangkih. Dan yang mengejutkan, naluri menolong sesama yang tumbuh alami dalam dirinya, yang akhirnya menyelamatkan seorang lelaki yang ia temukan di hutan yang sama, dari amukan serigala—setelah sebelumnya ia tak melakukan apa-apa ketika gerombol serigala itu mencabik seorang perempuan lain yang juga berada di tempat yang sama hingga tubuhnya tak berbentuk. Peristiwa yang membuat batin Renee bergulat dengan semacam perasaan bersalah, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk dirinya sendiri, semacam rasa menyesal, mengapa ia tidak menolong?
Bisakah kaurasakan bagaimana empati dengan sangat halus mulai menumbuh dalam diri Renee?
Perjalanan membawa Renee ke Mimms Selatan, sebuah perkampungan kecil di mana orang hidup bersama-sama dan saling berbagi serta melengkapi satu sama lain. Tempat di mana Renee disambut dengan hangat dan penuh kasih sayang. Ia menerima segenap perlakuan yang memunculkan rasa diinginkan, dibutuhkan, diapresiasi, dan disayangi, seperangkat rasa yang membuat manusia merasa lebih hidup dan berarti.
Kehidupan membuka tabirnya. Renee yang telah mampu melebur ke dalam masyarakat kecil itu, dan hidup layaknya manusia penuh empati, ia menerima kenyataan bahwa selama ini hidupnya dimata-matai lewat avatarnya sendiri, oleh seseorang yang berkuasa menciptakan dunia simulasi demi mencari pasangan untuk memulai peradaban manusia kembali. Ia mencintai Renee, dan menginginkan Renee menjadi Hawa-nya untuk melahirkan anak-anak Adam (sekali lagi). Tapi Renee menolak. Ia marah. Ia berpikir ‘Sang Narator’ itulah yang telah mendorong orang-orang bunuh diri, termasuk ibunya sendiri.
Renee kembali ke Mimms Selatan, bercinta dengan manusia anjing—yang kini jauh lebih manusiawi—dan melahirkan anak-anak yang ia sebut ‘anak anjing’. Mengajarkan banyak hal di sekolah, termasuk pelajaran sejarah tentang kehidupan Individutopia di Kota London yang busuk. Dan pada suatu kesempatan membawa beberapa anak muda desa untuk mengunjungi Kota London, serupa mengunjungi museum.
Renee akhirnya menerima kenyataan, pengemis yang kerap ia jumpai dan abaikan di jalan hampir setiap hari itu adalah ayahnya yang selalu berusaha memanggil namanya lewat udara yang mengantarkan gelombang suara seperti berbisik di telinganya. Dan kenyataan pahit bahwa pertemuan itu adalah akhir dari hidup ayahnya yang sudah lama menderita kelaparan. Mati dipangkuannya dengan damai. Lalu kembali terdengar udara berbisik…”Rah… Rah… Renee… Ah… Putriku… Ah… Jangan khawatir, aku tak apa… Ah… Mari, anakku, bawa aku pulang…”
Bab-bab terakhir dari kisah Renee, bagiku tidak sebegitu mendebarkan dan semenggelisahkan seperti bab-bab awal, bab-bab pertengahan membawa pikiran pada hening—penuh perenungan. Seperti menyaksikan bagaimana alam bekerja, awal mula peradaban dibangun kembali setelah ‘reset’…
Bab terakhir begitu bersahaja, namun menurutku justru menjadi bagian paling penting. Sebuah penekanan dan penegasan suasana di mana ‘nilai kemanusiaan’ kembali eksis (sekali lagi). Begitulah aku kira, meski banyak orang begitu terkagum-kagum dengan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan yang nyaris, sekali lagi, nyaris bisa melakukan apa saja layaknya manusia, aku yakin, akan tiba masanya kemanusiaan akan kembali dirindukan.
***
Pada akhirnya sampai pada kesimpulan awal—semacam celah untukmu memasuki buku ini: ketika hari-harimu hanya sekumpulan rutinitas menjemukan, dengan ritme yang terus meningkat dan kian sukar ditaklukkan, engkau menjelma layaknya mesin yang dijalankan secara autopilot. Mengejar dan dikejar (entah apa). Seakan hantu terus mengawasi dari dalam kepalamu sendiri. Hidup kehilangan makna sejati. Tiap detik adalah angka yang mesti dibayar untuk mempertahankan sirkulasi udara di paru—agar tetap hidup dan punya daya untuk berkompetisi dengan manusia ‘mesin’ lainnya dalam jutaan grafik yang menghitung apa saja.
Hidup adalah catatan utang yang panjang dan terus bertambah tiap hirup napas dan derap langkah, ketika setiap keping bumi serta segala isinya telah habis dikapitalisasi.[*]
Yeni Purnama Sari, penyair. Saat ini berdomisili di Payakumbuh. Buku puisinya, Berumah di Kesunyian.



















